Buku Empire of AI karya Karen Hao merupakan potret mendalam tentang bagaimana mimpi besar menciptakan kecerdasan buatan demi kemanusiaan berubah menjadi proyek kekuasaan global yang dikendalikan oleh segelintir elit teknologi. Melalui riset jurnalistik selama bertahun-tahun dan wawancara dengan lebih dari tiga ratus narasumber, Hao menelusuri jejak Sam Altman—CEO OpenAI—sebagai figur sentral dalam kisah transformasi idealisme menjadi imperium digital. Buku ini tidak sekadar mengisahkan sejarah perusahaan teknologi, melainkan juga menggugat secara moral dan politis bagaimana artificial intelligence (AI) kini berfungsi layaknya bentuk baru kolonialisme modern, yang menjarah data, tenaga kerja, dan sumber daya alam atas nama kemajuan.
Buku ini dibuka dengan bab prolog yang menegangkan, “A Run for the Throne”, menggambarkan drama besar di balik kudeta internal OpenAI pada November 2023. Saat itu, dewan direksi OpenAI secara tiba-tiba memecat Sam Altman dengan alasan “tidak jujur secara konsisten terhadap dewan.” Peristiwa ini mengguncang dunia teknologi. Dalam waktu lima hari, terjadi kekacauan besar: Microsoft sebagai investor utama turun tangan, ribuan karyawan menandatangani surat protes, dan tekanan publik memaksa dewan menyerah. Akhirnya Altman kembali menjabat sebagai CEO, dan para anggota dewan yang dianggap “melawan” disingkirkan. Hao menggunakan episode ini untuk menggambarkan inti masalah yang ingin ia kupas: siapa sebenarnya yang berkuasa dalam menentukan masa depan AI—manusia secara kolektif, atau segelintir korporasi yang memiliki sumber daya?
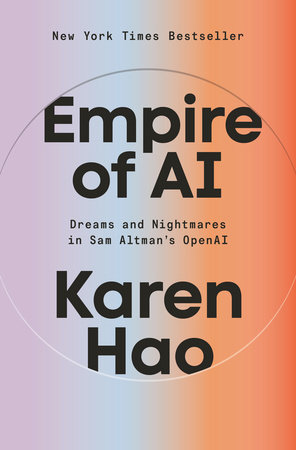
Dalam bagian pertama, Divine Right, Hao menelusuri awal mula hubungan Elon Musk dan Sam Altman yang melahirkan OpenAI pada tahun 2015. Saat itu, keduanya memiliki visi besar: mengembangkan Artificial General Intelligence (AGI) yang aman dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. OpenAI dilahirkan sebagai lembaga nirlaba yang menjunjung transparansi dan kolaborasi ilmiah. Namun, seperti yang ditunjukkan Hao, sejak awal sudah ada kontradiksi mendasar. Musk dan Altman tidak hanya ingin menciptakan AI; mereka ingin mengendalikan arah evolusi teknologi itu sendiri. Musk melihat dirinya sebagai pelindung manusia dari “AI jahat,” sementara Altman melihat peluang untuk membangun sistem kekuasaan baru berbasis kepercayaan dan pengaruh. Ia bukan insinyur, melainkan seorang strategist dan narrative builder—seseorang yang pandai menciptakan keyakinan dan loyalitas. Hao menggambarkan Altman sebagai sosok karismatik yang mampu membuat orang percaya bahwa ia sedang menyelamatkan dunia, padahal pada saat yang sama ia sedang membangun kekuasaannya sendiri.
Bagian kedua, Ascension and Corruption, menunjukkan bagaimana idealisme OpenAI mulai runtuh setelah Elon Musk keluar pada tahun 2018. Altman menghadapi krisis pendanaan besar karena penelitian AI memerlukan biaya miliaran dolar untuk komputasi dan data. Solusinya adalah mengubah struktur OpenAI menjadi entitas “capped-profit” bernama OpenAI LP—secara hukum masih di bawah yayasan nirlaba, tetapi secara praktik beroperasi seperti perusahaan profit. Keputusan ini membuka jalan bagi masuknya Microsoft sebagai investor besar dengan modal awal satu miliar dolar pada tahun 2019. Sejak saat itu, kata “open” dalam OpenAI kehilangan maknanya. Penelitian yang dahulu terbuka kini menjadi rahasia, dan idealisme “AI untuk semua” berubah menjadi kompetisi kecepatan demi mendominasi pasar. Hao menyebut fase ini sebagai “the corruption of mission,” ketika bahasa moral tentang kemanusiaan hanya menjadi perisai bagi ekspansi korporasi.
Bagian ketiga, Empire and Exploitation, merupakan inti kritik sosial dalam buku ini. Hao membedah bagaimana kesuksesan luar biasa ChatGPT yang diluncurkan pada November 2022 tidak berdiri di ruang hampa. Di balik wajah ramah chatbot itu, terdapat rantai produksi global yang penuh ketimpangan. Data yang digunakan untuk melatih large language models diambil dari internet secara masif tanpa izin pencipta aslinya—dari karya seniman, penulis, hingga jurnalis. Ribuan pekerja di Kenya, Filipina, dan Venezuela dibayar murah untuk melakukan pekerjaan yang disebut data labeling: menyaring gambar dan teks yang berisi kekerasan atau pornografi agar sistem AI “belajar” membedakan konten baik dan buruk. Hao menyebut mereka sebagai “digital proletariat” yang tak pernah disebut dalam narasi kemajuan teknologi. Sementara itu, data centers yang menopang AI mengonsumsi listrik dan air dalam jumlah besar, menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah seperti Arizona dan Chile. Bagi Hao, pola ini menyerupai kolonialisme klasik—bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan computation dan data extraction.
Pada bagian keempat, Reckoning, Hao kembali ke peristiwa kudeta 2023 untuk menunjukkan kegagalan total sistem governance OpenAI. Eksperimen struktur “nonprofit yang mengawasi perusahaan profit” ternyata tidak mampu menahan kekuatan modal dan loyalitas karyawan kepada figur karismatik seperti Altman. Dalam pandangan Hao, OpenAI telah menjadi simbol dari collapse of accountability dalam industri teknologi: keputusan tentang masa depan umat manusia dibuat dalam rapat-rapat tertutup oleh orang-orang yang tidak dipilih secara demokratis. Ironisnya, organisasi yang didirikan untuk “menyelamatkan dunia dari AI yang berbahaya” justru melahirkan sistem yang nyaris tak dapat dikontrol oleh siapa pun.
Hao kemudian memperluas analisisnya ke skala global. Di banyak negara berkembang, dampak ekspansi AI tidak hanya soal pekerjaan murah, tetapi juga krisis ekologis dan kultural. Di Kenya, pekerja yang menyaring data kekerasan mengalami trauma psikologis berat. Di Amerika Latin, sumber daya air terkuras untuk mendinginkan server. Di dunia kreatif, ribuan seniman kehilangan pendapatan karena karya mereka dijadikan bahan pelatihan model AI tanpa izin. Hao menulis bahwa “AI does not eliminate work—it redistributes exploitation.” Teknologi yang dijanjikan akan meringankan beban manusia justru memperlebar jurang ketimpangan antara mereka yang memiliki mesin dan mereka yang menjadi bahan bakarnya.
Meski begitu, di bagian epilog bertajuk How the Empire Falls, Hao tetap menyisakan secercah harapan. Ia menolak pandangan bahwa dominasi korporasi besar seperti OpenAI, Google, atau Anthropic adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ia mengusulkan model pengembangan AI yang lebih kecil, transparan, dan berkelanjutan—yang berfokus pada kebutuhan nyata manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan iklim. Hao menyerukan agar masyarakat global membangun tata kelola (AI governance) yang demokratis, dengan perlindungan terhadap data, hak cipta, dan tenaga kerja. Menurutnya, masa depan AI bukan ditentukan oleh kecepatan inovasi, melainkan oleh keberanian moral manusia untuk menata kembali kekuasaan teknologi.
Secara keseluruhan, Empire of AI bukan sekadar biografi Sam Altman atau sejarah perusahaan OpenAI. Ini adalah cermin bagi dunia tentang bagaimana mitos “AI for humanity” berubah menjadi ideologi kekuasaan. Hao menunjukkan bahwa di balik setiap lompatan teknologi terdapat relasi sosial dan ekonomi yang timpang—bahwa kecerdasan buatan, jika tidak diawasi, akan menjadi instrumen kekuasaan yang memperpanjang dominasi lama dalam bentuk baru. Kalimat terakhir buku ini menegaskan pesan moralnya: seperti halnya imperium masa lalu yang akhirnya tumbang oleh sistem yang lebih inklusif, masa depan AI pun masih bisa kita rebut bersama—asal kita berani mempertanyakan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas kecerdasan yang katanya “untuk semua umat manusia.”